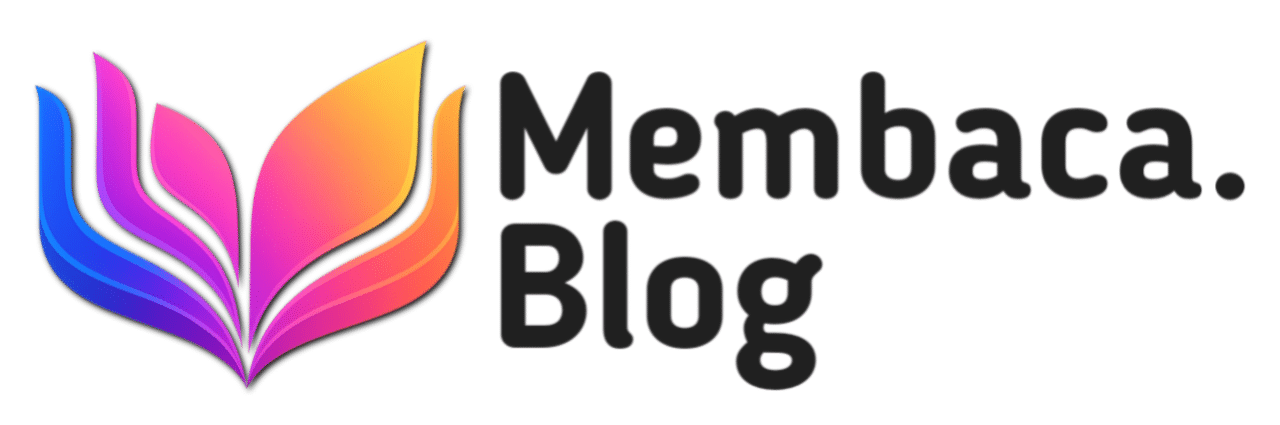Asam Askorbat
Asam askorbat (C₆H₈O₆), yang juga dikenal sebagai vitamin C, adalah senyawa organik larut air yang termasuk dalam kelompok lakton polihidroksil tak jenuh. Molekulnya berbentuk cincin lima karbon dengan ikatan rangkap pada atom karbon C2 dan C3 serta empat gugus hidroksil di posisi C2, C3, C5, dan C6. Rumus kimianya adalah C₆H₈O₆, dengan massa molar sekitar 176,12 g/mol. Pada kondisi murni asam askorbat berupa padatan kristalin berwarna putih kekuningan yang mudah larut dalam air. Senyawa ini terkenal karena sifat antioksidannya yang kuat, ia mudah menyumbangkan elektron atau proton untuk menetralisir radikal bebas, sehingga melindungi sel dari kerusakan oksidatif.
Asam askorbat pertama kali diisolasi pada 1928 oleh ilmuwan Hungaria Albert Szent Györgyi, yang kemudian dianugerahi Nobel Kimia tahun 1937 atas temuannya. Nama “askorbat” berasal dari kata a- (tanpa) dan scorbutus (skorbut), mengacu pada peran senyawa ini mencegah penyakit skorbut akibat defisiensinya. Pada awal penemuannya, senyawa ini sempat disebut asam heksuronat, namun kemudian dinamakan asam askorbat.
Struktur kimianya berhasil ditentukan oleh Walter Norman Haworth, sehingga ia menerima Hadiah Nobel Kimia 1937 bersama Paul Karrer atas pengungkapan struktur kimia berbagai vitamin, termasuk vitamin C. Haworth dan koleganya kemudian berhasil mensintesis secara kimia vitamin C untuk pertama kalinya, menjadikan asam askorbat vitamin pertama yang diproduksi secara massal.

Secara fisik, asam askorbat merupakan bubuk kristalin putih kekuningan. Pada gambar di atas terlihat sampel asam askorbat murni (bagian putih) dan bagian yang telah teroksidasi (berwarna kuning). Senyawa ini mudah teroksidasi oleh udara, sehingga perubahan warna menjadi kekuningan merupakan tanda terbentuknya produk oksidasi seperti asam dehidroaskorbat.
Asam askorbat bersifat asam lemah, dengan pKa pertama sekitar 4,10. Pada pH tubuh, ia sebagian terionisasi menjadi bentuk ion asorbat. Sebagai padatan, ia memiliki titik lebur sekitar 190–192 °C dan densitas sekitar 1,65 g/cm³. Kelarutannya tinggi dalam air (±33 g per 100 mL air pada suhu kamar), tetapi tidak larut dalam pelarut organik seperti dietil eter, kloroform, atau benzena.
Asam askorbat tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia karena manusia kekurangan enzim L-gulonolakton oksidase, sehingga vitamin ini harus diperoleh dari makanan atau suplemen. Kebutuhan harian vitamin C diperkirakan sekitar 75–90 mg untuk dewasa, dan lebih tinggi pada perokok atau wanita hamil. Sumber makanan kaya vitamin C meliputi buah jeruk (jeruk dan lemon), buah beri (stroberi dan acerola), pepaya, kiwi, serta sayuran seperti paprika merah/hijau, brokoli, dan tomat.
Beberapa buah tropis bahkan mengandung kadar asam askorbat yang sangat tinggi, misalnya kakadu plum ~5300 mg per 100 g dan acerola ~1600–1700 mg per 100 g. Setelah dikonsumsi, asam askorbat diserap di usus melalui transport aktif ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh, di mana ia dapat masuk ke berbagai sel melalui transporter khusus (SVCT1/SVCT2).
Dalam tubuh, asam askorbat berperan sebagai koenzim dan kofaktor penting bagi banyak reaksi enzimatik. Terutama dikenal sebagai kofaktor bagi enzim hidroksilase prolin dan lisin, yang diperlukan untuk hidroksilasi residu-prolin dan lisin pada biosintesis kolagen. Aktivitas ini krusial untuk pembentukan jaringan ikat yang sehat, tanpa vitamin C, kolagen tidak terbentuk sempurna dan penyembuhan luka terganggu. Selain itu, asam askorbat berperan dalam sintesis neurotransmiter (noradrenalin) dan beberapa hormon peptida, serta membantu proses pematangan molekul lain.
Kemampuannya sebagai antioksidan juga mendukung fungsi imun dan kesehatan vaskular, ia membantu mempertahankan integritas pembuluh darah, memperkuat sel endotel, menurunkan oksidasi LDL kolesterol, dan meningkatkan aktivitas sel darah putih dalam melawan infeksi. Secara keseluruhan, asam askorbat diperlukan untuk banyak fungsi biologis normal seperti penyembuhan luka, pertahanan terhadap stres oksidatif, dan pemeliharaan sel-sel tubuh lainnya.
Karena perannya sebagai vitamin esensial, kekurangan asam askorbat menyebabkan penyakit skorbut. Gejala kekurangan vitamin C termasuk kelemahan umum, mudah lelah, nyeri otot dan sendi, gusi bengkak dan berdarah, hingga luka sulit sembuh. Selain skorbut, defisiensi kronis dapat berkontribusi pada masalah kesehatan lain seperti peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dan gangguan imunitas.
Di sisi lain, konsumsi asam askorbat berlebihan juga dapat menimbulkan efek samping. Dosis yang sangat tinggi dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, kram perut, mual, dan muntah. Meskipun demikian, toksisitas akut sangat rendah karena vitamin C bersifat larut air dan mudah diekskresikan melalui urin, nilai LD₅₀ (dosis letal 50%) pada tikus dilaporkan sekitar 11,9 g/kg (oral), menunjukkan batas yang jauh di atas dosis nutrisi biasa.
Secara industri, asam askorbat diproduksi terutama melalui proses Reichstein, yaitu metode kombinasi kimia-mikroba dari glukosa dalam lima tahap. Proses ini mengubah glukosa menjadi sorbitol, kemudian menjadi L-sorbosa melalui fermentasi bakteri, dan selanjutnya melalui beberapa reaksi oksidasi dan deproteksi membentuk asam 2-keto-L-gulonat yang dilaktonisasi menjadi L-askorbat.
Metode Reichstein modern telah mengalami optimasi tinggi, dan saat ini bioteknologi fermentasi memungkinkan produksi 2-keto-L-gulonat secara langsung dalam dua langkah, memperpendek proses sintesis kimia. Selain itu, garam asam askorbat (misalnya natrium askorbat) juga banyak digunakan sebagai sumber vitamin C yang lebih stabil dalam produk makanan dan suplemen.
Dalam praktik pangan dan farmasi, asam askorbat digunakan sebagai aditif makanan (E300) untuk mencegah oksidasi (menunda tengik minyak) dan mempertahankan warna makanan. Ia juga dikonsumsi sebagai suplemen diet untuk memastikan kebutuhan vitamin C tercukupi. Penggunaan terapeutik utama adalah pencegahan dan pengobatan skorbut. Dalam beberapa penelitian modern, dosis tinggi asam askorbat juga diteliti kemungkinannya dalam mendukung pengobatan penyakit tertentu melalui aksi antioksidan dan imunitas, meskipun penggunaannya harus hati-hati memperhatikan potensi efek samping.
Daftar Referensi :
- Szent-Györgyi, A. (1928). Isolation of Ascorbic Acid. Journal of Biological Chemistry, 78(1), 305–317.
- Haworth, W. N., & Karrer, P. (1937). Constitution of Ascorbic Acid. Journal of the Chemical Society, 1937, 599–607.
- Reichstein, T. (1934). The Reichstein Process for Vitamin C Production. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 67(1), 105–110.
- National Center for Biotechnology Information. (2025, July 1). Ascorbic Acid. PubChem Compound Database.
- Office of Dietary Supplements, National Institutes of Health. (2024, November 5). Vitamin C Fact Sheet for Health Professionals.
- U.S. Food and Drug Administration. (2023, March). Code of Federal Regulations Title 21 – Vitamin C (E300).
- World Health Organization; Food and Agriculture Organization. (1988). Vitamin C in Human Nutrition. WHO Technical Report Series No. 505.
- Linus Pauling Institute, Oregon State University. (2025, June). Pharmacology and Therapeutic Uses of Vitamin C.
- Pullar, J. M., Carr, A. C., & Vissers, M. C. M. (2017). The Roles of Vitamin C in Skin Health. Journal of Cosmetic Dermatology, 16(4), 680–687.
- Carr, A. C., & Maggini, S. (2017). Vitamin C and Immune Function. Nutrients, 9(11), 1211.
- European Food Safety Authority. (2014). Scientific Opinion on the Re-evaluation of Ascorbic Acid (E 300). EFSA Journal, 12(11), 3523.
- Levine, M., Conry-Cantilena, C., Wang, Y., Welch, R. W., Washko, P. W., Dhariwal, K. R., … Cantilena, L. R. (1996). Vitamin C Pharmacokinetics in Healthy Volunteers: Evidence for a Recommended Dietary Allowance. American Journal of Clinical Nutrition, 64(6), 1150–1157.
- Padayatty, S. J., Katz, A., Wang, Y., Eck, P., Kwon, O., Lee, J. H., … Levine, M. (2003). Vitamin C as an Antioxidant: Evaluation of Its Role in Disease Prevention. Journal of the American College of Nutrition, 22(1), 18–35.
- Carr, A. C., & Frei, B. (1999). Toward a New Recommended Dietary Allowance for Vitamin C Based on Antioxidant and Health Effects in Humans. The American Journal of Clinical Nutrition, 69(6), 1086–1107.
- Battino, M., Ferreiro, M. S., Gallardo, I., Newman, H. C. T., & Pittalà, V. (2009). The Effect of Vitamin C on Human Health. International Journal for Vitamin and Nutrition Research, 79(3), 127–134.